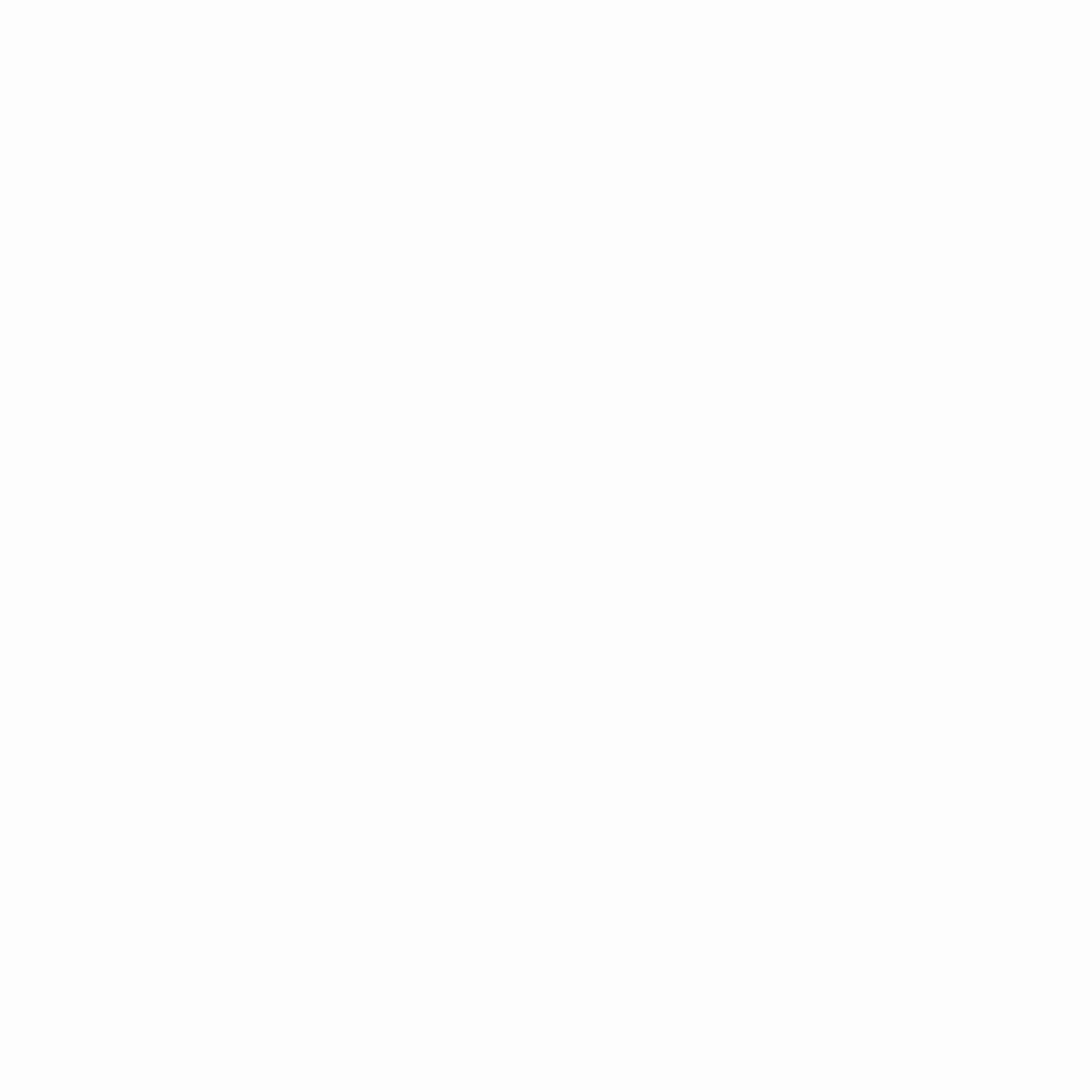Stacked Line, Photo by Oldblue Co.
Nyaris satu dekade silam, ada sebuah masa dimana saya menghabiskan sekian jam di depan layar komputer setiap harinya. Berselancar di sebuah situs forum jual beli, dari satu penjual ke penjual lainnya. Mencari harga terbaik sekaligus menghitung-hitung kembali nominal yang tersedia di rekening saya. Tak lupa untuk menghitung resiko finansial yang menghantui di kemudian hari jika saya memutuskan untuk membelanjakannya.
Lucunya, barang yang saya idamkan, saat itu adalah jeans Nudie replika, alias palsu, alias kawe. Era 2010-2011 rasanya memang masa keemasan brand tersebut di tanah air. Ketertarikan terhadap sneakers yang berujung pada fashion secara keseluruhan, ditambah sang sobat (haqqy251, warga forum DB juga) yang terlebih dahulu mengakuisisi Nudie Thin Finn menjadi tekanan sosial tersendiri untuk saya.
Akan tetapi entah mengapa, dan menjadi hal yang saya syukuri hingga saat ini, keinginan tersebut tak pernah terealisasi. Kondisi ekonomi saya pada itu relatif terbatas, bahkan untuk sekedar mengakuisisi barang palsu. Seiring memulai “karir†sebagai warga DB, spirit untuk mendukung produk-produk otentik pun perlahan mengikis keinginan tersebut. Meskipun, daftar hawa nafsu kian bertambah seiring gelombang referensi baru yang menghujam.
Tibalah satu waktu, secara tak terduga saya mendapatkan sejumlah uang yang cukup besar dari seorang sanak famili, untuk ditabung ujarnya. Saya yang masih jauh dari kata literasi finansial, dengan mudahnya terbakar hebat. Tak lama setelahnya saya berpetualang di berbagai situs untuk pre-purchase research, pilihan jatuh kepada Pure Blue Japan XX-005 yang saya jemput langsung di The Denim Vault (R.I.P) Kemang. Tak lupa pula aksesoris pendukung, seperti bifold wallet dari Monkeycatfish dan belt Voyej bermahkota natural vegetable tanned sebagai pasangan sejatinya.
Di luar sedikit penyesalan akan uang yang tak terasa menguap begitu saja, saya masih ingat betul perasaan yang luar biasa campur aduk saat pertama kali merendam celana tersebut ke air panas. Aroma khas nan asing, air yang perlahan menjadi coklat seiring lunturnya starch, bahan yang mengeras seraya melunturkan warna birunya, semua terekam jelas, tak pernah mati.
Setelah mengunggah celana kesayangan di thread “New Pickup (Denim)†dan “Fit Descriptions & Picturesâ€, maka petualangan baru secara resmi dimulai. Terkadang saya malu mengingatnya, tapi masa-masa itu termasuk masa “jahiliyah†dalam fase hidup saya. Kuliah terlantar, pun ditolak sekolah penerbangan negeri dan swasta, detik ke detik, hari demi hari habis begitu saja di hadapan layar komputer warnet. Beruntung setidaknya saya berhasil sedikit berkontribusi untuk menyumbangkan medali sebagai penghias interior warnet, setidaknya.
Beberapa bulan berselang, rencana liburan bersama para kolega SMA pun menggema. Beruntung, masih ada sisa-sisa kejayaan pasca kalap beberapa bulan silam yang memungkinkan saya turut berpartisipasi dalam perjalanan ini. Perjalanan ini menjadi momen penting pertama bersama celana kesayangan, selain hanya sekedar duduk manis di kursi warnet dan tongkrongan. Perjalanan yang menjadi titik tolak, momen yang mempertemukan saya pada dunia menulis, tertuang manis pada tautan ini dan ini untuk Anda yang belum berkesempatan untuk menyimaknya.

Kalian mungkin pernah, atau barangkali sedang mengalami fase dimana kalian terobsesi “ukiran†whiskers dan honeycomb kontras yang terangkum manis di thread “Evolution of Jeans : PICS and appreciations†dan forum lainnya. Ingin rasanya jika lekukan-lekukan garis indah tersebut turut terpatri di jeans kita.
Segala kerelaan pun tak sungkan kita berikan. Sebut saja aroma dan sentuhan tak nyaman karena mitos pantang cuci sebelum enam bulan, mengenakannya dibanding celana pendek yang jauh lebih nyaman saat terlelap, dan menempuh ratusan bahkan ribuan kilometer menuju garis pantai hanya untuk tampak seperti orang kurang kerjaan (baca: seawash).
Tidak, tidak, sebelum kalian mengerenyitkan dahi karena penyataan menyebalkan saya soal kurang kerjaan, saya tidak bermaksud untuk menghina maupun menghakimi hal-hal tersebut, pun saya pernah berada di fase tersebut. Karena pada akhirnya setiap orang punya makna untuk setiap stimulus yang menghampiri inderanya, menjadi sebuah realita yang berjalan pada zona waktunya masing-masing, dimana hanya kalian (dan Tuhan) yang betul-betul memahaminya.
Pada realita yang terjadi dalam kaca mata saya pribadi, seiring waktu berjalan saya akhirnya memahami bahwa setiap raw denim akan terkikis, mengukir pola, memiliki penanda khas yang merepresentasikan karakter dan kehidupan pemakainya. Sebut saja noda-noda yang menghiasi celana jeans setiap orang. Cipratan cat akrilik pada celana jeans mahasiswa seni rupa, noda oli untuk para penggila motor tua, atau mungkin noda kecoklatan yang cukup besar dan begitu enggan terkikis bagi sang penakluk alam liar.
Belum lagi jika kita berbicara mengenai pola fades yang terukir. Seiring waktu pun saya memahami bahwa setiap orang akan memiliki pola fades yang unik dan berbeda. Sandingkan dua raw jeans dengan merek, tipe, dan ukuran yang sama untuk digunakan oleh dua orang berbeda. Sejauh kita berusaha untuk menyamakan frekuensi penggunaan, perawatan, dan kegiatan yang dilakukan, pada akhirnya kita akan menemukan fakta bahwa lekukan fades yang dihasilkan akan tetap berbeda.
Perlahan, akhirnya saya memahami bahwa raw denim sangatlah relevan dengan konsep “tabula rasa†(kertas kosong, dalam bahasa latin) yang lahir dari buah pemikiran Aristoteles. Konsep yang merujuk pada pandangan epistemologi bahwa manusia dilahirkan tanpa isi mental bawaan alias “kosongâ€, layaknya kanvas putih yang akan terlukis oleh pengalaman dan perjalanan hidup seiring waktu berjalan.
Lewat konsep yang hadir di kelas Psikologi Komunikasi, semester dua tersebut saya belajar bahwa selama ini saya berusaha keras menjadi “orang lain†hanya demi ukiran fades yang tentunya fana, dan bersifat permukaan. Momen pembelajaran itu menjadi sebuah titik pergeseran makna raw denim dalam kehidupan saya.
Sejak saat itu saya tak sungkan melemparkan celana jeans saya ke dalam mesin cuci saat terlihat kotor dan mulai terasa lengket. Tak ada lagi rasa takut saat terpaksa menghadapi hujan yang turun tak terduga. Tak ada lagi bau tak sedap dan jamur yang hinggap di antara sudut-sudut lembab pada jeans saya. Hidup terasa lebih mudah, saya perlahan menjadi diri saya sendiri yang risih akan pakaian kotor dan memaknai bahwa pakaian seharusnya memudahkan, bukan menyulitkan hidup manusia.
Terima kasih ibu Feliza Zubair, Aristoteles, dan John Locke atas pencerahannya.
Saya mengajak kalian untuk coba ingat bagaimana rupa raw jeans pertama kalian yang muncul dari dalam bungkusan, atau kalian jemput sendiri di toko maupun ajang tahunan kita Wall of Fades. Pekat warna indigo di setiap inci-nya, aroma dan bulu-bulu halus katun yang beterbangan, rongga-rongga yang sedikit mengganggu kenyamanan rasa dan estetika di minggu-minggu pertama pemakaian.
Tengoklah kondisinya saat ini, mungkin sejenak kalian akan teringat apa-apa saja yang menjadi momen indah, konyol, atau bahkan menyedihkan saat kalian mengenakan celana tersebut. Tanpa kita sadari, seonggok celana tersebut melebur dalam kehidupan kita. Dia hadir bersama cinta yang bersemi, dalam gelak tawa bersama orang-orang yang berarti, serta tangis dalam harap yang tak menemui takdirnya. Mengukir pengalaman kita dalam liukan garis indah yang dahulu begitu kita dambakan rupanya.
Minggu sore yang cerah ini, saya yang sedang kebingungan untuk menyelesaikan paragraf penutup artikel ini pun tak pernah menyangka, bahwa raw denim dapat membawa sejumput nilai-nilai kehidupan yang penuh arti. Lebih dari sekadar gengsi label harga jutaan rupiah, produksi terbatas, dan hal-hal bersifat permukaan lainnya. Lebih jauh lagi, terkandung sebuah substansi, menjadikannya sebuah “kanvas”, merefleksikan hidup kita yang unik dan berbeda satu sama lain dalam rentang waktu tertentu.
Hingga tiba saat rentang berikutnya, terpaksa ataupun rela, menutup kisah manis lalu yang terukir abadi, dan bersiap untuk membuka lembaran baru.
Alias beli jeans baru, hehe.